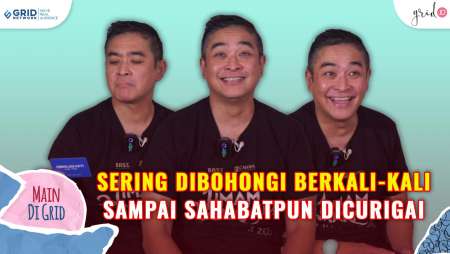Baca Juga: Sempat Ramai Dibicarakan Orang Sewaktu Dipilih Sebagai Pejabat Pertamina, Rupanya Jokowi Berikan Hal yang Tak Disangka Itu Jadi Tantangan Utama Buat Sosok Kontroversial Ini: Negara Lagi Kurang Uang? Meski demikian, sejatinya gesekan antara Indonesiadan Uni Eropa terkait sawit sudah dimulai sejak cukup lama.
Sebagaimana yang telah diketahui, Benua Biru merupakan salah satu blok ekonomi yang menaruh perhatian sangat besar terhadap isu-isu lingkungan. Tak heran mengingat sebagian besar negara-negara di Eropa masuk dalam kategori high-income economies, yaitu yang memiliki pendapatan per kapita lebihdari US$ 12.376/tahun, berdasarkan data Bank Dunia (World Bank/WB). Masyarakat yang tinggal di negara berpendapatan tinggi memang cenderung lebih mudah untuk menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan. Pasalnya, kebutuhan 'perut' mereka sudah terpenuhi, sehingga punya waktu lebih untuk memikirkan hal lain. Berbeda dengan negara berkembang yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi.

Jokowi Resmikan Tol JORR II ruas Kunciran-Serpong
Komitmen Uni Eropa (UE) terhadap lingkungan sejalan dengan Protokol Kyoto, yaitu mengurangi emisi karbon sebesar 20%. Untuk itu, UE mengeluarkan kebijakan biofuel (biodiesel dan bioethanol) pertama yang dikenal sebagai Renewable Energy Directive (RED) pada tahun 2003 (2003/30/EC). Tujuannya adalah untuk menggantikan posisi energi fosil dengan energi terbarukan. Uni Eropa memasang target penggunaan biofuel untuk transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010. Akan tetapi kenyataan tidak seindah harapan. Pada tahun 2005, nyatanya Uni Eropa hanya mampu memenuhi 1,4% biofuel pada sektor transportasi. Penyebabnya, peraturan tersebut tidak bersifat mengikat alias sukarela.
Baca Juga: Berdiri Sewaktu Presiden Soeharto Berkuasa, BUMN Misterius Ini Bikin 2 Menteri Jokowi Cuma Bisa Melongo. Lantas, Kenapa Tiba-tiba Badan Usaha Negara Itu Jadi Sorotan? Selanjutnya pada tahun 2007, Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Roadmap yang isinya merubah target yang sebelumnya telah ditetapkan. Salah satunya adalah 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi energi pada tahun 2020, serta 10% biofuel untuk transportasi pada tahun 2020. Roadmap ini juga mengubah status 2003/30/EC menjadi mengikat dan wajib, sehingga dapat lebih mudah dikontrol. Sejatinya saat itu, hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa semakin bagus. Pasalnya negara-negara Eropa boleh melakukan cara apapun untuk memenuhi target biofuel, termasuk impor dari negara lain.
Namun kondisi tersebut berubah mulai tahun 2009. Saat Uni Eropa mulai merevisi peraturan RED (2003/30/EC) menjadi 2009/28/EC. Revisi tersebut mengatur syarat-syarat biofuel yang bisa digunakan di Uni Eropa. Salah satu poin yang paling penting adalah mengatur tentang bahan berkelanjutan (sustainable) yang bisa digunakan sebagai bahan baku biofuel. Dijelaskan bahwa produk biodiesel harus terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Uni Eropa tidak akan memperhitungkan biofuel yang berdampak padakerusakan lingkungan.
Baca Juga: Bilang Biasa Berpanas-panasan, Staf Khusus Presiden yang Juga Anak Pengusaha Terkaya Ini Ternyata Mulai Ketularan Kebiasaan Jokowi. Dia Pun Dapat Setumpuk PR dari Sang Presiden! Salah satu yang dianggap merusak lingkungan adalah tanaman yang ditanam pada lahan bekas pembabatan hutan yang dilakukan pasca Januari 2008. Ada pula aturan teknis mengenai spesifikasi bahan baku, proses pembuatan, hingga dampaknya untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Syarat-syarat tersebutlah yang selanjutnya menuai polemik. Pasalnya banyak pihak beranggapan bahwa syarat tersebut merupakan bentuk hambatan perdagangan non-tarif. Jelas saja, dengan adanya syarat yang sangat sulit untuk diadaptasi oleh produsen, Uni Eropa seakan sudah membatasi negara-negara yang boleh memasukkan biofuel ke Benua Biru. Contohnya, petani sawit Indonesia yang biasa mengirim minyak sawit ke Uni Eropa (untuk bahan baku biodiesel) kan tidak bisa sekonyong-konyong merelokasi lahan tanam. Terlebih saat itu beredar anggapan bahwa sawit Indonesia telah berkontribusi sangat besar terhadap perusakan hutan (deforestasi).
Selain itu, minyak sawit yang mau masuk ke Uni Eropa juga harus melalui proses sertifikasi yang berbelit-belit.
Terlebih mulai tahun 2016, Uni Eropa merancang target-target baru dalam kebijakanenergi terbarukan, yang dikenal sebagai RED II. Dalam RED II ditetapkan bahwa target penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 naik menjadi 32% dari yang semula 27%. Diatur pula kontribusi beberapa kategori biofuel sehingga tidak melebihi konsumsi tahun 2019. Kategori yang dimaksud adalahyang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land-Use Change/ILUC), serta tanaman yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan.
Bahkan dalam aturan tersebut disebutkan bahwa minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai bahan yang tidak berkelanjutan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel. Penggunaan sawit akan dikurangi secara bertahap hingga habis sama sekali pada tahun 2030. Peraturan tersebut mulai tertuang dalam revisi RED II 2018/2001/EU, pada Desember 2018 dan diberlakukan Komisi Eropa pada Maret 2019. Hal itulah yang membuat Indonesia dan Malaysia, sebagai penghasil 85% sawit dunia naik pitam.
Khususnya di Indonesia, industri sawit merupakan lapangan usaha lebih dari 4 juta petani kecil. Kala ekspor dihambat dengan peraturan-peraturan non-tarif tersebut, akan ada banyak petani yang merasakan dampaknya. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit, seperti dikutip dari detikfinance. Gugatan akan dilakukan melalui World Trade Organization (WTO).

:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227030128.jpg)